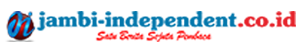Menakar Kebijakan Fiskal Penyelamat Alam

Ilustrasi. Foto udara pemandangan Bukit Lawang, di Bahorok, Langkat, Sumatera Utara, kawasan yang menyimpan keaneragaman hayati. -ANTARA-
Di banyak negara, keberhasilan pajak jenis ini justru ditentukan oleh koordinasi antarlembaga, bukan semata besaran tarifnya.
Inggris, misalnya, menerapkan biodiversity net gain (BNG) yang mewajibkan setiap proyek pembangunan memberikan peningkatan biodiversitas, minimal 10 persen, sebelum izin diberikan.
Kebijakan ini hanya berjalan efektif jika ada sinkronisasi antara otoritas perencanaan, lembaga lingkungan, dan sistem monitoring berbasis satelit.
Australia, melalui environmental offset policy juga menunjukkan bahwa integrasi data ekologis nasional dengan izin industri dapat mengurangi risiko manipulasi offset dan memastikan pajak lingkungan terhubung dengan rencana tata ruang.
Sementara Belanda menerapkan skema ecological compensation yang terhubung langsung dengan kebijakan air dan tata ruang, membuat pajak lingkungan berfungsi efektif untuk melindungi ekosistem delta yang rentan.
Jika sinkronisasi semacam ini lemah, pajak dapat kehilangan fungsi korektifnya, atau bahkan membuka ruang bagi manipulasi data dan tumpang tindih kebijakan.
Dalam jangka panjang, pajak ini dapat menjadi sumber baru pembiayaan lingkungan. Program restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, pemulihan DAS, konservasi spesies, dan penguatan kawasan penyangga, selama ini, sebagian besar bergantung pada APBN reguler yang terbatas.
Dengan sumber pajak khusus, beban fiskal dapat dialihkan dari sektor-sektor vital menuju skema pembiayaan lingkungan yang lebih mandiri dan stabil.
Lebih jauh, jika sebagian penerimaan dialokasikan kembali ke daerah, maka pemerintah daerah akan memiliki insentif fiskal untuk menjaga kualitas ekosistemnya.
Hal ini relevan dengan isu TKD, saat ini, di mana banyak daerah mengeluhkan formula transfer pusat yang belum cukup mempertimbangkan kinerja ekologis dan kualitas tata ruang.
Selama ini, TKD lebih banyak ditautkan dengan indikator dasar, seperti populasi, tingkat kemiskinan, atau kapasitas fiskal.
Sementara faktor ekologis, misalnya rasio tutupan hutan, tingkat degradasi lahan, atau kerentanan ekologis belum sepenuhnya masuk dalam skema insentif.
Dengan memasukkan pajak atas kehilangan keanekaragaman hayati sebagai sumber pendapatan yang dapat direalokasikan ke daerah berbasis kinerja lingkungan, Indonesia dapat menciptakan model green fiscal decentralization yang lebih adil dan efektif.
Daerah yang menjaga tutupan hutan, mengurangi deforestasi, dan memperbaiki ekosistem akan mendapat tambahan transfer, sementara daerah dengan tingkat degradasi tinggi terdorong melakukan koreksi kebijakan.
Pendekatan ini bukan hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga menyelaraskan pembangunan nasional dengan keberlanjutan ekologis jangka panjang.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: