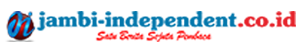Jurnalisme adalah Terapi yang Dibayar

Ilustrasi. Seorang jurnalis harus mampu membaca situasi, menjaga jarak, dan menahan diri.-ist/jambi-independent.co.id-
Kerja jurnalistik sering digambarkan sebagai praktik yang “belajar sambil jalan”. Hanya saja, ungkapan itu kerap terdengar terlalu ringan untuk menjelaskan beban kognitif yang sesungguhnya.
BACA JUGA:Penjualan Mobil LCGC Jeblok 30%, Menperin Angkat Bicara, Astra Ungkap Realita Pasar
Dalam perspektif sosiologi profesi, jurnalisme dapat dipahami sebagai bentuk continuous professional learning, proses belajar yang tidak pernah selesai karena medan kerjanya terus berubah.
Donald Schon, dalam gagasannya tentang the reflective practitioner, menjelaskan bahwa profesi yang berhadapan dengan situasi tak pasti menuntut kemampuan refleksi terus-menerus di dalam tindakan.
Jurnalis bekerja dalam ruang semacam itu: informasi datang tidak utuh, waktu terbatas, tekanan hadir bersamaan. Keputusan editorial diambil bukan dari rumus baku, melainkan dari penilaian reflektif yang diasah melalui pengalaman berulang.
Maka metafora “sekolah tanpa bel pulang” menemukan pijakan teoretisnya. Setiap liputan berfungsi sebagai kelas baru; setiap naskah sebagai ujian yang kerap datang mendadak.
BACA JUGA:Nekat di Perumahan Elit! Maling Bobol Alfamart, CCTV Disemprot Cat dan Uang Rp20 Juta Raib
Koreksi redaktur bukan sekadar penyuntingan teknis, melainkan mekanisme evaluasi, rapor atas cara berpikir, ketepatan sudut pandang, dan ketahanan argumen.
Proses ini membentuk habitus profesional, yang meminjam istilah Pierre Bourdieu, tertanam melalui praktik harian, bukan melalui ceramah normatif.
Sekolah ini tidak memiliki kurikulum eksplisit tentang kerja emosional. Padahal, Arlie Hochschild mengingatkan bahwa banyak profesi modern menuntut emotional labor: kemampuan mengelola perasaan agar selaras dengan tuntutan peran.
Jurnalis diharapkan empatik tanpa larut, kritis tanpa sinis, dan objektif tanpa beku. Keseimbangan itu dipelajari secara implisit, melalui koreksi, teguran, dan pengalaman lapangan, bukan melalui modul resmi.
Tekanan kecepatan di era digital mempertebal kompleksitas tersebut. Ruang refleksi menyempit, sementara tuntutan akurasi tetap tinggi.
Di sinilah kerja belajar jurnalis menjadi berlapis: ia belajar fakta, belajar konteks, sekaligus belajar mengatur ritme berpikirnya sendiri.
Sekolah tanpa bel pulang ini tidak menawarkan kelulusan, hanya kompetensi yang terus diuji. Dan justru karena itu, jurnalisme menuntut kesiapan mental yang kerap luput dari pengakuan formal.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: